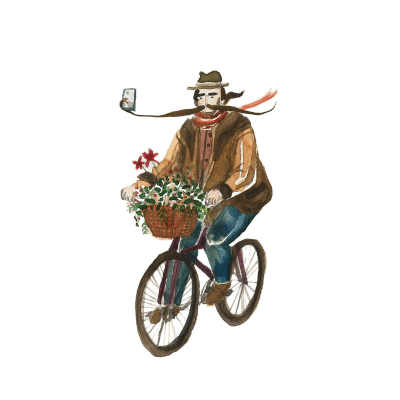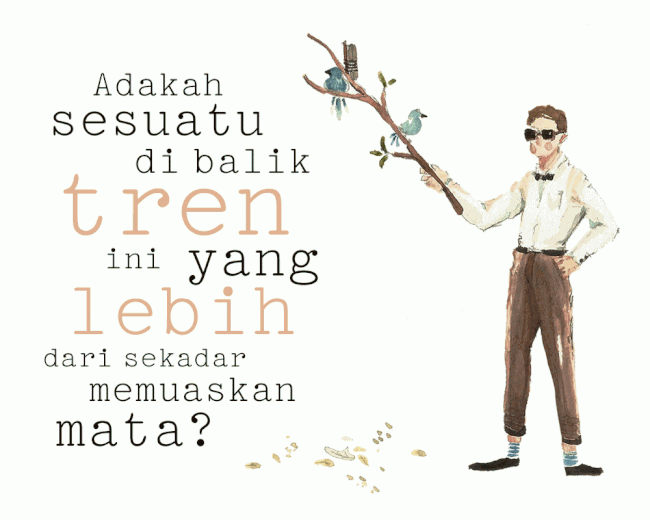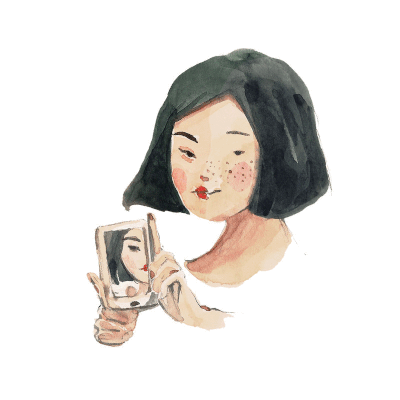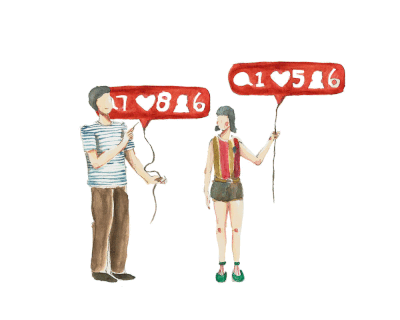Ketika Hubunganku Menentukan Identitasku
Penulis: Larissa Segara
Mungkin kamu pernah mendengar kisah tentang seekor anak rajawali yang dibesarkan oleh induk ayam. Sehari-hari ia bergaul dengan anak ayam, makan seperti mereka, berjalan seperti mereka. Ketika suatu hari ia mengagumi burung rajawali yang terbang melintasi langit dengan gagahnya, induk ayam berkata, “Itu rajawali. Mereka hidup di atas. Jangan berpikir untuk menjadi seperti rajawali. Mereka berbeda dengan kita, ayam, yang hidup di bawah.” Sampai akhir hidupnya, si anak rajawali pun tetap hidup seperti ayam.
Kisah itu sering dipakai sebagai ilustrasi yang menggambarkan betapa tragisnya bila orang hidup tidak sesuai dengan identitasnya. Namun, tidak bisa dipungkiri, sebagai orang-orang yang sudah ditebus Kristus, seringkali kita pun menjalani hidup yang tidak mencerminkan identitas baru kita di dalam Kristus. Termasuk diriku.
Hampir enam tahun lamanya aku membiarkan hubunganku menentukan identitasku. Aku merasa hidupku tidak utuh tanpa seorang pria di sampingku. Aku pun tak ragu menjalin hubungan dengan seorang yang tidak seiman. Awalnya, hubungan kami tidak begitu serius, namun sangat menyenangkan. Aku sempat berpikir, lama-lama aku bisa mempengaruhinya dan mendorongnya memiliki keyakinan yang sama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Makin lama, aku justru makin merasa bergantung padanya. Aku mulai menjauh dari keluarga, teman-temanku, bahkan dari Tuhan. Hidupku kuberikan sepenuhnya untuk pacarku, dan aku merasa tidak bisa hidup tanpa dia. Aku menyadari ada yang salah dengan hidupku. Pacarku sudah menjadi berhala hidupku. Tetapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa tidak sanggup menjalani hari-hariku sendirian. Bahkan ketika hubungan kami mulai renggang, dan ia ingin mengakhirinya, aku tidak mau melepasnya. Kami sudah pernah membicarakan rencana-rencana di masa depan, dan aku tidak mau rencana-rencana itu hancur. Jadi, aku berusaha mempertahankan hubunganku dengannya.
Saat hubungan kami berjalan lima tahun lebih, aku harus pergi ke luar kota selama dua bulan. Ia juga harus pergi ke luar negeri. Banyak hal menyakitkan yang ia lakukan. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku mengetahui bahwa ia selingkuh. Berhari-hari aku memohon kekuatan dari Tuhan agar aku bisa keluar dari relasi ini. Lalu dengan berat hati, aku memutuskan hubungan dengannya.
Kehilangan pacar membuat aku merasa hidupku tidak normal lagi. Aku merasa kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Setiap hari aku bangun pagi dengan jantung berdebar kencang, takut, dan cemas. Tidak ada damai sejahtera. Nafsu makanku hilang dan aku tidak ingin melakukan apa pun. Di satu sisi, aku sulit memaafkan mantan pacarku. Di sisi lain, aku sering mengingat dan ingin mengulangi kebersamaan kami di masa lalu, sekalipun aku tahu itu tidak benar di mata Tuhan. Seperti bangsa Israel yang sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir, namun masih saja suka membanding-bandingkan kehidupan mereka yang baru dengan kehidupan lama mereka di Mesir. Di dalam diriku seperti ada peperangan yang terus-menerus. Aku ingin berdoa, tetapi Iblis mendakwa aku setiap waktu bahwa aku tidak layak kembali kepada Tuhan, karena aku telah menyakiti-Nya dengan ketidaktaatanku.
Bukan suatu kebetulan, pada titik terendahku itu, gerejaku mengadakan doa puasa selama setahun (seminggu tiap bulannya). Gembala kami mendorong setiap jemaat untuk ikut berdoa dan berpuasa, memohon kekuatan dari Tuhan. Aku pun mulai berpuasa (sebelumnya tidak pernah), dan bersaat teduh secara teratur (sebelumnya aku hanya berdoa sebagai rutinitas biasa). Aku mulai melihat bagaimana pengalaman itu diizinkan Tuhan terjadi supaya aku bertumbuh secara rohani. Tuhan mengajar aku untuk mengasihi Dia lebih dari yang lain, mengajar aku untuk memaafkan, dan menyelamatkan aku dari masa depan yang bukan dari-Nya. Aku bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Mazmur 34:19 berkata bahwa “Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya”. Firman Tuhan ini mematahkan kebohongan Iblis yang berusaha menjauhkan aku dari Tuhan.
Tanpa terasa bulan demi bulan berlalu. Aku terus berdoa memohon kekuatan, damai sejahtera, dan penghiburan. Di suatu sore yang mendung dan sepi, saat sedang berdoa, tiba-tiba aku merasakan sukacita yang besar memenuhi hatiku. Aku tahu bahwa meskipun situasiku tidak akan pulih dalam sekejap, Tuhan sedang terus memulihkan dan memperbarui diriku. Di dalam hadirat-Nya, Tuhan selalu memberikan aku kekuatan baru.
Hari ini, dalam anugerah Tuhan, aku dapat dengan yakin berkata bahwa identitasku tidak ditentukan oleh hubungan-hubungan yang kumiliki. Aku tidak menjadi orang yang lebih baik atau lebih buruk karena kehadiran seorang pacar. Identitasku ditentukan oleh Tuhan, Pencipta dan Pemilik hidupku. Adakalanya iblis berusaha membuatku ragu dengan identitasku sebagai orang yang telah ditebus, namun firman Tuhan menjadi senjataku untuk mematahkan serangannya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati untuk menebus kita dari kuasa dosa, sehingga setiap kita yang percaya kepada-Nya dapat memiliki identitas baru sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Allah (Yohanes 1:12; 1 Petrus 2:9).
Aku berharap kamu juga diteguhkan oleh kebenaran ini.