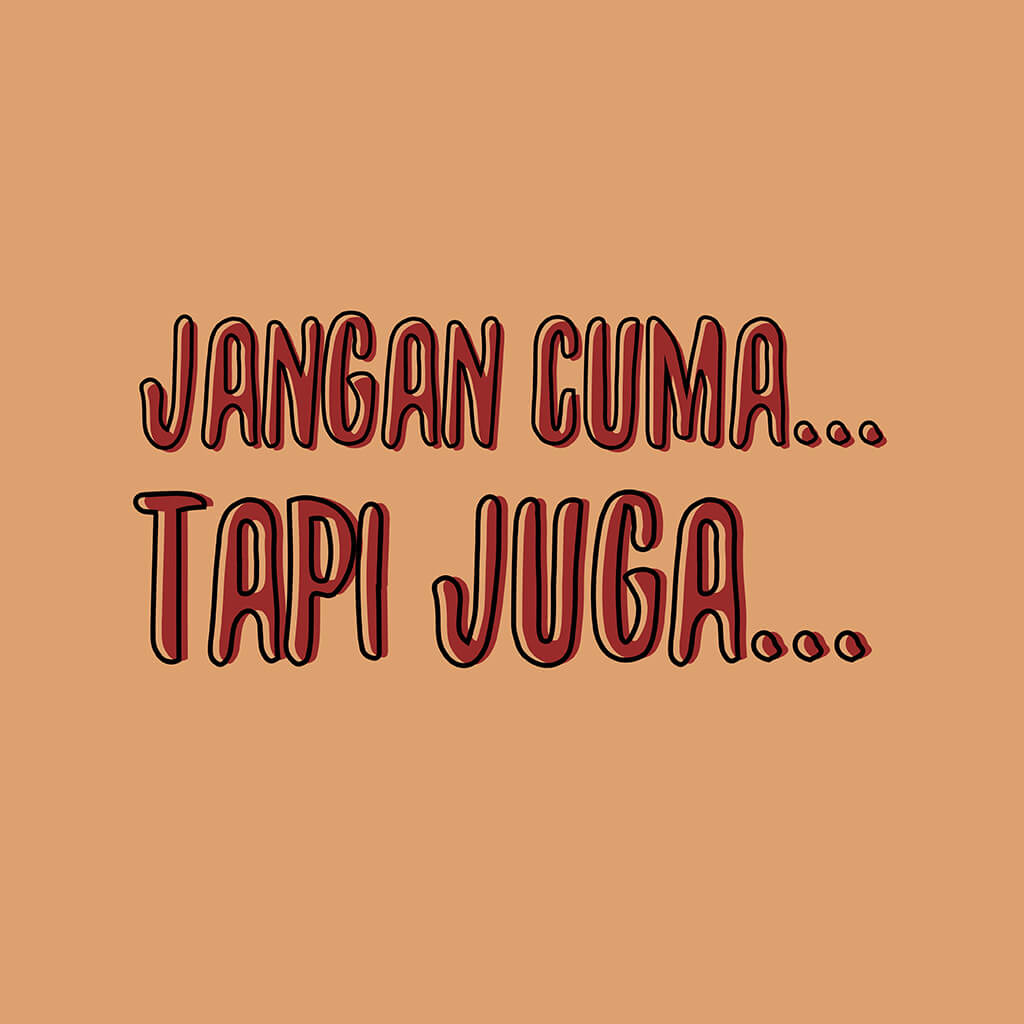Hal yang Kulupakan Ketika Aku Asyik Menggunakan Instagram Story

Oleh Lidya Corry Tampubolon, Jakarta
Sekitar setahun lalu, Instagram menciptakan inovasi baru yang sangat digemari oleh para penggunanya hingga saat ini: Instagram Story—yang sering disingkat menjadi Instastory ataupun Snapgram. Melalui fitur ini, kepada followers-nya, seseorang bisa membagikan gambar dan video yang dapat diedit terlebih dahulu secara real-time atau dalam waktu yang hampir bersamaan saat peristiwa tersebut terjadi.
Awalnya, seperti kebanyakan teman-temanku, aku menikmati fitur Instastory dengan cukup aktif. Setiap harinya aku bisa mengunggah 1-5 konten pada Instastoryku. Namun, sampai di satu titik, aku memutuskan untuk berhenti menggunakan fitur ini hingga waktu yang tidak ditentukan. Alasan aku berhenti menggunakan Instastory bukanlah karena fitur ini salah. Akan tetapi, aku berhenti karena kelemahanku sendiri, yang mungkin juga merupakan kelemahan bagi banyak orang, yaitu self-esteem, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai “harga diri”.
Jika ditilik lebih dalam, melalui bacaan dari Wikipedia maupun beberapa jurnal psikologi yang pernah kubaca, pada dasarnya self-esteem berarti bagaimana seseorang menilai harga dirinya sendiri.
Dalam pergumulanku pribadi, aku merasa bahwa Instastory telah merusak caraku menilai harga diriku sendiri.
Aku cenderung menempatkan dan mencari harga diriku melalui pengakuan-pengakuan dan pandangan dari orang lain. Ketika zaman beralih menjadi digital, cara yang paling mudah dan efektif untuk ‘menghitung’ harga diriku adalah melalui media sosial. Instastory memberiku kesempatan untuk meliput kehidupanku secara real-time. Para followers-ku bisa mengetahui apa yang sedang aku kerjakan, apa yang sedang aku makan, apa yang sedang aku rasakan, dan banyak hal lainnya melalui tiap-tiap gambar atau video yang kuunggah.
Inilah hal yang menurutku membuat Instastory lebih berbahaya daripada media sosial lainnya seperti Path, Facebook, ataupun Twitter. Melalui visual dan audio yang disajikan secara real-time, tanpa sadar aku telah menjadikan Instastory sebagai sarana untukku memamerkan kehidupanku kepada orang lain. Aku bisa menunjukkan betapa menyenangkannya aktivitas yang kulakukan, betapa enak dan mahalnya makanan yang aku makan, betapa sibuk dan kerennya pekerjaanku, dan banyak hal lainnya.
Tanpa kusadari, aku berjuang untuk melihat diriku terlihat lebih berharga dengan memamerkan kehidupan yang kujalani. Aku jadi sangat tergoda untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain tentang betapa kerennya dan menyenangkannya hidupku. Bahkan, seringkali, tanpa kusadari aku ingin supaya orang lain iri melihat diriku dan kehidupanku.
Sebenarnya, bukanlah hal yang salah untuk mencari dan menemukan harga diri. Dalam pandangan dunia, self-esteem adalah hal yang penting karena hal ini akan mendorong manusia termotivasi untuk menjalani hidupnya. Bahkan, Abraham Maslow, seorang psikolog yang juga teoritikus menempatkan self-esteem atau harga diri sebagai peringkat kedua dalam piramida kebutuhan psikologis manusia.
Jadi, sebenarnya tidak ada yang salah dengan self-esteem selama kita mencarinya di tempat yang benar. Namun, sayangnya adalah dunia kita saat ini telah kehilangan tempat mencari self-esteem yang benar.
Dalam pergumulanku saat itu, aku membaca sebuah artikel berjudul “Find Your Self-esteem in Someone Else” yang ditulis oleh Jon Bloom. Kutipannya adalah sebagai berikut:
Sekitar pergantian abad ke-20, teori tentang “self-esteem” muncul di bidang psikologi, dan pada tahun 1960 teori ini diterima oleh budaya Barat dan dianggap sebagai salah satu akar utama dari kesehatan mental. Tetapi sesungguhnya teori ini tidak mengatasi masalah mendasar, yaitu keterpisahan dari Allah. Setelah lebih dari 50 tahun mencoba menerapkan teori ini sebagai obat untuk penyakit kita akan identitas, kita mendapati bahwa diri kita hanya semakin terisolasi dan hubungan kita dalam komunitas dan masyarakat hanya menjadi lebih retak. Semua ini terjadi karena kita kita mencari harga diri kita di tempat yang salah dan untuk alasan yang salah.
Perjuanganku untuk menaikkan nilai harga diriku melalui pengakuan dan penghargaan dari orang lain melalui media sosial sesungguhnya berasal dari keterpisahanku dengan Allah. Sadar atau tidak sadar, seringkali aku merasa tidak ada seorangpun yang bisa ataupun mau mengapresiasi, menghargai, mengasihi, dan mengakui diriku kalau aku tidak tampil menawan di hadapan orang lain. Hal ini jelas tidaklah benar. Alkitab dengan jelas mengatakan:
“Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu” (Yesaya 43:4).
“Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguhpun demikian tidak seekorpun dari padanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamupun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak burung pipit” (Lukas 12:6-7).
Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa diriku begitu berharga di hadapan-Nya. Aku diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sang pencipta alam semesta. Bahkan, kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak sedikitpun menghilangkan kasih-Nya kepadaku dan juga kepada seluruh umat manusia. Kita tetap dipandang-Nya berharga, begitu berharga hingga Allah sendiri melalui Yesus Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita.
“Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa” (Roma 5:8).
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” (Yohanes 3:16).
Mungkin bagi beberapa orang, ayat-ayat di atas terasa seperti hapalan di luar kepala. Namun, ayat tersebut adalah bukti nyata bahwa kasih-Nya kepada kita telah dinyatakan di atas kayu salib. Darah-Nya yang tercurah sudah membuktikan betapa berharganya aku dan kamu di hadapan Allah.
Harga diriku tidak ditentukan dari seberapa banyak likes atau comment yang aku dapatkan di tiap-tiap gambar atau story yang kuunggah. Harga diriku dan harga dirimu begitu mahal, seharga darah yang telah Yesus curahkan untuk menebus dosa-dosa kita.
Pada akhirnya, aku sadar bahwa ketika aku menggunakan Instastory dan media sosial lainnya, seharusnya aku tidak mencari harga diriku di sana. Harga diriku tidak ditemukan pada media sosial. Harga diriku yang sesungguhnya hanya kutemukan pada salib Kristus.
“Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat” (1 Petrus 1:18-19).
Baca Juga:
Ketika Keraguan akan Imanku Membawaku Pada Yesus
Aku dilahirkan di keluarga bukan Kristen yang cukup taat beribadah. Bahkan, kedua orangtuaku pernah menyekolahkanku di sebuah sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Namun, sampai di satu titik, aku mulai meragukan iman yang kupercayai yang pada akhirnya menuntunku kepada Yesus.