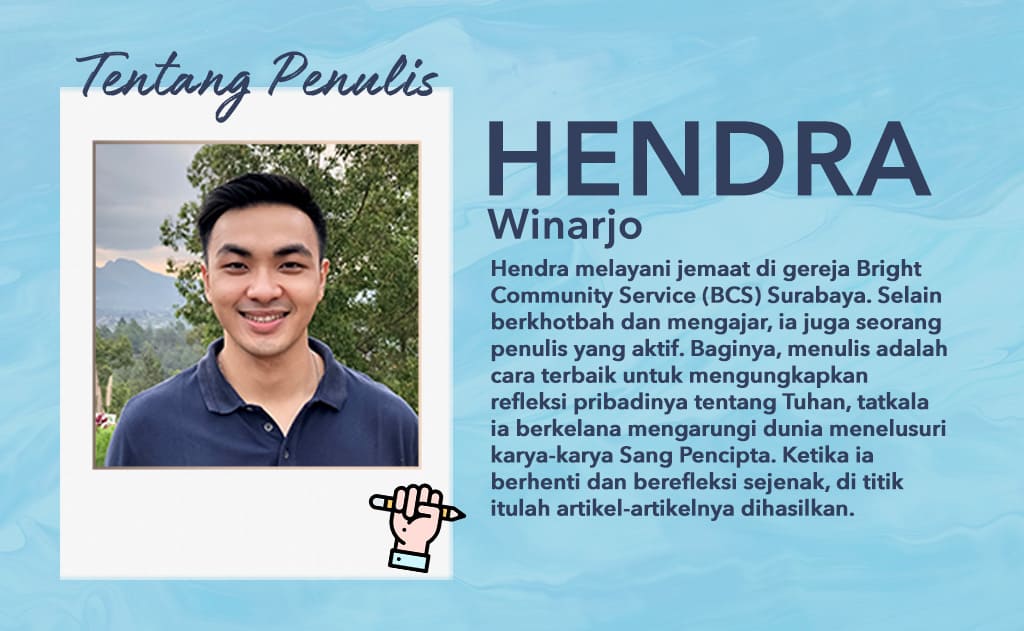Oleh Olivia E.H, Jakarta
Ketika kecil, aku suka menghibur diri dengan berbagai kisah mitologi Yunani di perpustakaan sekolah. Salah satu yang paling berkesan buatku adalah dongeng tentang Persephone dan Hades. Begini ceritanya:
Persephone dikenal sebagai dewi musim semi, dia adalah putri dari Demeter, dewi pertanian. Dalam narasi mitologi paling mainstream dan klasik, dewa Hades selaku penguasa dunia bawah jatuh cinta pada kecantikan Persephone. Tanpa seizin Demeter, Hades menculik Persephone dan membawanya tinggal bersama di dunia bawah.
Demeter sangat sedih dan marah karena kehilangan putrinya. Dia mencari Persephone ke seluruh dunia, tetapi tidak berhasil menemukannya. Karena kesedihannya, tanah-tanah menjadi tandus dan tak ada tumbuhan yang hidup.
Melihat kesengsaraan yang timbul di bumi akibat kesedihan Demeter, akhirnya Hades mengizinkan Persephone kembali ke bumi selama setengah tahun yang melambangkan musim semi dan panen.
Dongeng tentang Persephone di masa sekarang pun dimaknai ulang oleh beberapa seniman visual. Persephone tidak semata digambarkan sebagai damsel in distress alias korban pasif yang tiba-tiba saja diculik, tetapi dia dilihat sebagai sosok wanita yang berdaya dan bisa mengambil keputusannya sendiri.
Dalam tafsiran para kreator modern, Demeter dianggap menaruh berbagai harapan dan idealismenya pada Persephone hingga sang putri pun muak dan memilih hidup di dunia bawah bersama Hades. Tapi, kok bisa ya? Bagaimana mungkin sosok dewi yang merepresentasikan musim semi bisa bahagia di antara orang mati?
Demeter yang berekspektasi tinggi berharap Persephone akan jadi “duplikat” dirinya. Ketika akhirnya Persephone hilang, Demeter sedih dan marah hingga nyaris membunuh satu bumi dengan tidak mau menumbuhkan apa pun.
***
Seru rasanya ya membahas cerita dongeng kuno. Tapi, di tulisan ini aku mau mengajakmu untuk melihat, memahami, dan bagaimana kita bisa menanggapi orang tua yang seringkali memaksakan ekspektasinya kepada anak-anak mereka.
Aku lahir di keluarga yang bisa kukatakan banyak masalah. Suatu ketika saat aku SMP, aku akan pergi ke mall untuk jalan-jalan sekaligus photobox bareng teman sekelas. Rencana sudah matang dibuat, namun ketika aku akan berangkat, orang tuaku bertengkar di rumah. Di usia ketika aku mencari validasi diri, disuguhkan pemandangan keributan membuatku ingin cepat kabur. Kakakku yang tahu aku akan pergi main bersama teman, ikut mengomel: “Rumah lagi begini, kamu bisa jalan-jalan sama temen?! Batalin!”
Kakakku yang usianya enam tahun di atasku punya harapan padaku untuk mengikuti jejak langkahnya menjadi “penjaga” keluarga. Padahal, aku lebih ingin menjadi “pengelana.”
Di kesempatan berbeda, aku mulai belajar untuk mencernah ekspektasi-ekspektasi lain. Orang tuaku berharap aku jadi anak yang tidak menyusahkan, atau melipur kekecewaan mereka akan pernikahannya. Kakakku sering berkata betapa ia bahagia dengan kehadiranku sebagai adik, karena ia berharap mendapat teman setim untuk menghadapi orang tua.
Seiring berjalannya waktu, ekspektasi bergulir. Ketika aku bekerja kantoran, orang tuaku menganggapnya tidak keren karena tidak jadi pengusaha. Ketika aku merintis usaha sendiri, dibanding-bandingkan terus hasilnya dengan gaji orang kantoran. Selain urusan kerja, orang tuaku juga menuntutku untuk rajin dan aktif di gereja yang harus sealiran dengannya. Bahkan urusan selera makan dan hobi olahraga pun aku dipaksa untuk sama seperti mereka.
Ekspektasi-ekspektasi yang menuntut itu mendorongku bertemu dengan konselor. Di satu sesi konselingku, dia berkata, “Kebahagiaan keluargamu bukan tanggung jawabmu. Kamu tahu itu, kan? Kebahagiaan sejati seseorang yang sudah dewasa seharusnya lahir dari dalam dirinya sendiri, bukan karena perbuatan atau sikap orang di luar dirinya, bahkan meskipun itu anak sendiri.”
Aku melihat sikap orang tuaku dalam mengasuh anak-anak mereka sebagai pola asuh yang tidak baik, atau mungkin bisa dikategorikan sebagai pola pengasuhan toksik. Dalam pola asuh ini, orang tua seringkali menggunakan kekuasaan, kontrol, dan manipulasi untuk mempengaruhi dan mengendalikan. Mereka mungkin memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap anak, sehingga mengabaikan kebutuhan dan perasaan anak, serta seringkali memberikan hukuman fisik atau verbal yang tidak pantas.
Dalam pengasuhan toksik, orang tua seringkali tidak memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Mereka mungkin mengharapkan anak untuk selalu memenuhi harapan dan standar mereka, tanpa memperhatikan keunikan dan potensi anak itu sendiri. Akibatnya, seorang anak bisa merasa tidak berharga, tidak dihargai, dan kurang percaya diri. Bahkan perasaan negatif ini bisa bertahan hingga remaja dan dewasa.
Namun, bukan berarti orang tua tidak boleh berekspektasi terhadap anaknya. Memiliki ekspektasi atau harapan terhadap sosok yang kita kasihi adalah natur manusia yang wajar. Ekspektasi yang realistis dan sehat justru jadi bagian penting dalam perkembangan anak dan untuk mewujudkannya diperlukan cara-cara yang suportif.
Literatur Kristen melalui Alkitab memberiku role model ibu-anak yang lebih positif dan empowering, bahkan meskipun tanpa ikatan darah. Dua tokoh ini tidaklah asing buat kita, mereka adalah Rut dan Naomi.
Rut adalah menantu Naomi. Setelah kematian suami dan anak-anak Naomi, Rut memilih tetap setia pada ibu mertuanya dan menganggapnya seperti ibu kandungnya sendiri. Kasih sayang yang tulus dari ibu mertualah yang membuat Rut bertahan. Berdua, mereka pergi bersama menuju petualangan terbesar dalam hidup.
Di kitab Rut pasal 1 ayat 16-17, Rut berkata kepada Naomi: “Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau dan untuk berbalik dari padamu; sebab ke mana engkau pergi, ke situ aku akan pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ aku akan bermalam. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, di situ aku akan mati dan di situ aku akan dikuburkan. Demikianlah TUHAN kiranya berbuat kepadaku, dan demikianlah ditambahnya, jikalau bukan hanya maut yang memisahkan aku dan engkau.”
Loyalitas, rasa hormat, dan kasih sayang Rut terhadap Naomi, merupakan teladan yang baik untuk relasi antara ibu dan anak. Hubungan mereka mencerminkan kehangatan, kasih sayang, dan komitmen yang ada dalam relasi ibu dan anak secara natural, tanpa paksaan. Naomi berekspektasi Rut akan meninggalkannya saja dan memulai hidup baru. Rut ternyata berekspektasi untuk ikut Naomi mudik. Naomi pun mau mengubah rancangan hidupnya dengan menyertakan Rut di dalamnya.
Dalam zaman sekarang, kita sering kali melihat kepahitan dalam relasi, terutama antara mertua dan menantu. Namun, kisah Rut dan Naomi mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki hubungan yang penuh kasih dan saling menghormati, meski ada saling ekspektasi di dalamnya.
Kisah ini mengingatkan kita bahwa relasi keluarga adalah tentang saling mendukung dan mengasihi, meski satu sama lain punya ekspektasi yang berbeda. Dengan saling menghormati ekspektasi satu sama lain, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan manis seperti Rut dan Naomi.
***
Tapi tapi tapi… Demeter & Persephone ‘kan mitologi Yunani kuno, dan Rut & Naomi adalah kisah sejarah Yahudi ribuan tahun lalu! Apa kabar dong buatku yang masih sering keselek karena sulit menelan ekspektasi orang tua hari ini?
We have to give agency to ourselves.
Frase “giving agency to ourselves” berarti memberikan kekuatan atau otoritas kepada diri kita sendiri. Dalam konteks psikologi, ini berarti bahwa kita mengakui dan menggunakan kekuatan kita sendiri untuk membuat keputusan, menentukan pilihan, dan mengendalikan arah hidup secara mandiri. Jadi, memberikan agency kepada diri kita sendiri berarti mengambil alih kendali atas hidup kita dan bertindak sesuai dengan keinginan, tujuan, dan nilai-nilai kita.
Namun, meskipun kita punya pilihan bebas untuk menentukan hidup kita sendiri, ingatlah bahwa identitas kita yang sejati ada di dalam Kristus. Dialah yang telah menebus kita dari dosa-dosa, sehingga ketika dunia mengatakan dan mendorong kita untuk menjadi diri sendiri sebebas-bebasnya sesuai dengan keinginan hati kita, meminjam kutipan dari Gregg Morse, kita bisa tanamkan pemahaman ini:
Don’t just be yourself. Be something greater. Be the version of you that Jesus died to create.
Jangan sekadar jadi dirimu sendiri, tetapi lebih dari itu. Jadilah dirimu yang ingin diciptakan Kristus lewat kematian-Nya.
Identitas kita di dalam Kristus memampukan kita menjadi anak-anak yang bijaksana, yang ketika menyuarakan isi hati kita tetap bertindak menghormati orang tua sebagai sosok yang mengasihi kita. Pengasuhan toksik yang mungkin kita alami bisa jadi adalah buah dari buruknya pengasuhan generasi di atas orang tua kita. Bagi kita yang telah mengenal firman dan juga diberkati dengan zaman di mana ilmu parenting dengan mudahnya tersedia, kelak saat kita menjadi orang tua, kita dapat belajar banyak untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti generasi di atas kita.
Jadi, ketika keluarga menyodorkan ekspektasi pada kita, tak perlu seketika emosi atau marah-marah. Sodorkan balik ekspektasi kita untuk mereka, lalu jalanin proses saling berinteraksi dengan sehat. Dan, yang tampak klise tetapi penting adalah doakan orang tua kita. Bukan semata-mata agar mereka berubah, tetapi agar baik kita dan mereka dikaruniakan hikmat dan kebijaksanaan untuk menimbang apa yang paling baik, untuk tetap mengutamakan kasih sebagai pengikat relasi. Jika ekspektasi itu berlandaskan kasih dan kita pun mengasihi mereka, pastilah akan ada solusi untuk menemukan jalan tengahnya.
Selamat menimbang dan mengunyah ekspektasi dari orang tua yang masuk sehari-hari dengan lebih berhikmat!
Kamu diberkati oleh artikel ini? Yuk dukung pelayanan WarungSaTeKaMu ♥